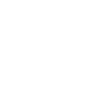

Negeri Krisis Literasi
Lupakan sejenak KKN. Indonesia sedang menghadapi krisis tidak kalah berat: krisis literasi.
Indonesia dalam keadaan SOS: Save Our Souls or Society. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca. Itu adalah jalur hidup bagi jiwa, akal, dan masyarakat. Tapi mulainya tetap dari membaca.
Hasil tes PISA sudah sering dikutip: 75% pelajar Indonesia usia 15 tahun tidak memahami informasi dasar dari bacaan. Tapi yang lebih mengkhawatirkan hasil studi OECD (2012–2015) di berbagai negara termasuk Indonesia.
Temuannya: Lulusan universitas di Jakarta memiliki kemampuan literasi yang lebih rendah dibanding lulusan SMA di negara-negara OECD. Sekitar 42% lulusan perguruan tinggi di Jakarta hanya berada pada level literasi paling dasar (Level 1 dari 6).
Bahkan, skor mereka setara dengan orang dewasa di OECD yang belum lulus SMA. Ini bukan sekadar anomali statistik. Ini tamparan nasional keras.
Di Indonesia, gelar akademik tidak menjamin literasi fungsional. Kenapa?
Jawabnya: input menentukan output. Jika 70–80% siswa SMA hanya memiliki literasi dasar, jangan harap kemampuan mereka akan melonjak tiba-tiba di bangku kuliah. Apalagi jika kampusnya pun berkualitas rendah.
Input lemah, proses lemah, hasilnya pasti lemah. Dan jika ini terus berlangsung, akan menciptakan lingkaran kebodohan permanen.
Krisis ini tidak muncul tiba-tiba. Literasi rendah di SMA adalah output literasi rendah di SMP. SMP mewarisi dari SD.
Jadi, perbaikannya harus dimulai dari hulu — SD. Tapi, hasilnya tak akan instan, perlu 8–10 tahun untuk terlihat. Dan setiap tahun kita menunda, kita menunda kualitas SDM nasional selama satu dekade. Temuan PISA menunjukkan skor literasi di SMP berkorelasi erat dengan produkvititas siswa setelah memasuki dunia kerja.
Seperti saya dokumentasi dalam buku Indonesian Dream (2009): Kita belum menjadi masyarakat pembaca. Buku belum menjadi bagian dari budaya utama kita. Survei BPS 2006 mengungkap: Hanya 13% penduduk usia 10+ membaca buku non-pelajaran.
Meski 20 tahun berselang, situasi praktis sama.
Membaca di Negeri Lain
Di AS, menurut laporan terbaru dari Scholastic’s Kids & Family Reading Report, rata-rata jumlah buku yang dibaca per tahun:
- Usia 6–11 (pembaca aktif): 43 buku
- Usia 6–11 (kurang aktif): 21 buku
- Usia 12–17 (pembaca aktif): 40 buku
Di Korea Selatan, siswa membaca rata-rata 36 buku per tahun (Menurut laporan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan).
Literasi adalah fondasi belajar dan produktivitas. Itu menentukan kemampuan numerasi, sains, hingga logika berpikir. Namun bagaimana meningkatkan literasi jika akses bacaan pun langka?
Laporan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (2019) mengungkap dua faktor utama rendahnya kualitas literasi nasional: akses dan budaya. Skornya menyedihkan: 23 dan 28 dari 100.
Budaya yang tidak antusias literasi tak akan menuntut ketersediaan bacaan. Akibatnya, bacaan pun tak tersedia. Dan sebaliknya. Jadi lingkaran setan.
Kita hidup di era sarat informasi, tapi belum menjadi masyarakat pembelajar. Yang muncul justru budaya bergosip, tanpa kedalaman berpikir kritis. Dan itu kita wariskan turun-temurun.

Sering kita menyalahkan korupsi sebagai akar masalah. Tapi bisa jadi sebaliknya: korupsi dan nepotisme adalah gejala dari akar yang lebih dalam—literasi yang lemah.
Literasi yang lemah membuat kita tidak benar-benar memahami apa yang kita tahu. Lebih parah lagi, membuat kita tak sadar atau tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Ini menjadikan masyarakat mudah dibohongi, gampang terpecah, dan sulit diajak berpikir kritis dan rasional.
Agenda Nomor Satu
Krisis literasi harus menjadi agenda nasional nomor satu. Bahkan lebih urgen daripada program makan siang gratis. Makan siang habis dalam sehari. Tapi literasi memberi pangan bagi pikiran seumur hidup. Tanpa literasi, makanan itu hanya mengenyangkan, tapi tidak mencerahkan.
Dan tanpa literasi, anak-anak kita akan tetap lapar—lapar pengetahuan, lapar nalar, dan lapar masa depan.
Atau, mengapa tidak keduanya? Makan siang untuk tubuh. Literasi untuk masa depan. Lewat program terarah, efektif, dan efisien.
Elwin Tobing, profesor ekonomi dan presiden INADATA di Irvine, AS, menginisiasi Gerakan LIFT (Literacy for the Future) sejak dua tahun lalu untuk membangun literasi dan karakter anak-anak Indonesia. Sebagai bagian dari Gerakan LIFT, ia menulis seri Misteri Luki & Fani (24 buku), dirancang khusus untuk siswa kelas 4–6 SD. Kisah petualangan bilingual ini menggabungkan edukasi dan hiburan, sambil menanamkan nilai, logika, sains, serta wawasan nasional dan global.
